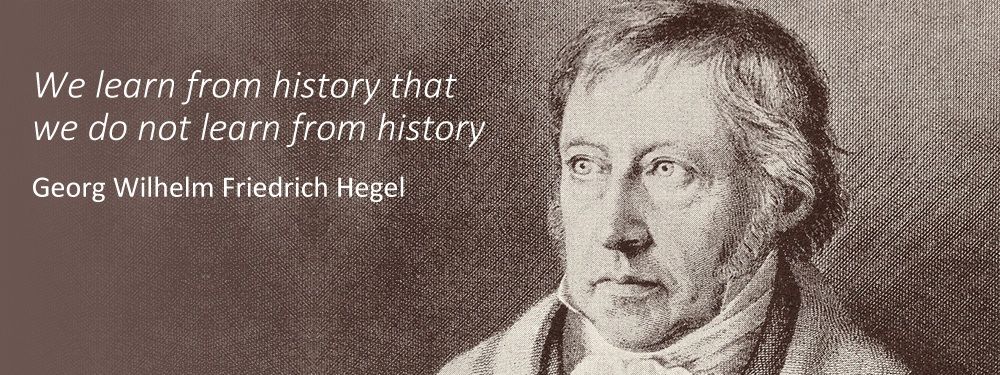Suara dari Balik Tirai Kegilaan
Di tulisan sebelumnya saya sudah menyinggung bagaimana lensa kehidupan bisa buram oleh kepura-puraan dunia. orang terjebak pada keadaan normalisasi kepura-puraan hanya untuk sama dengan orang lain. Kali ini, saya ingin mengajak teman semua benar-benar berkenalan dengan sosok yang menjadi “pemegang lensa besar” itu. Dalam kitab Uqala al-Majanin, Abu al-Qasim al-Naisaburi tidak sedang menulis catatan medis ala psikiatri modern. Bagi Naisaburi, kegilaan bukanlah soal kabel di otak yang putus. Ia justru sedang memotret sebuah kemerdekaan spiritual. Ia justru sedang memotret jiwa-jiwa yang paling sehat—karena berani memutus rantai ekspektasi sosial yang membelenggu.
Naisaburi bukan sekadar pengumpul kisah pengantar tidur ataupun cerita jenaka. Ia Hidup di abad ke-11 di Nishapur, pusat intelektual Islam kala itu, ia dikenal sebagai cendekiawan yang menguasai Al-Qur’an hingga filologi. Yang menarik, ia dekat dengan tradisi Karramiya—sebuah gerakan asketis yang menekankan pelepasan diri total, bahkan sampai pada praktik penyiksaan diri demi kesalehan. Dari latar ini, kita bisa memahami mengapa ia melihat “kegilaan” bukan sebagai malfungsi otak, melainkan sebagai keadaan spiritual: mabuk ilahi yang tampak irasional bagi mata duniawi.
Bahlul: Nasihat dari Gundukan Tanah
Salah satu fragmen paling ikonik adalah kisah Bahlul al-Majnun. Di mata penduduk Baghdad, ia tampak seperti paradoks berjalan: duduk di pemakaman, bermain dengan debu, berbicara sendiri. Namun ketika Khalifah Harun al-Rasyid meminta nasihat, Bahlul hanya menunjuk ke kuburan dan berkata: “Lihatlah istana mereka… dan lihatlah di mana mereka kini berada.” Nasihat itu sederhana, telanjang, tapi menghantam langsung ke ego manusia. Bahlul adalah “RAW file” kehidupan—jujur, apa adanya, tanpa filter pencitraan.
kisah Bahlul ini membuka pemahaman baru bagi saya bahwa gila itu bukanlah kondisi kehilangan kesadaran penuh. Pada sebagian orang, kegilaan yang disematkan pada mereka mungkin hanya label karena ketidakmampuan mangatur titik fokus pada kebijaksanaan orang (yang kita anggap) gila itu.
Baca juga: Kalibrasi Kewarasan Bagian 1: Lensa yang buram dan kepura-puraan yang rapi
Naisaburi mengingatkan, secara asal-usul kata, akal (‘aql) berarti “penahan”. Ia menahan kita dari kebodohan, tapi juga bisa menahan kita dari kejujuran. namun akal ini memiliki dua bilah. Akal mampu menghitung risiko sosial, menimbang untung-rugi, memecahkan masalah hingga menciptakan ide yang orisinil. walaupun banyak juga yang pada akhirnya kemampuan itu membelenggu keberanian untuk menjadi diri sendiri. Para Uqala al-Majanin adalah mereka yang berhasil memecahkan belenggu itu. Mereka menerima limpahan pengetahuan ilahi (warid) yang menembus hati, melampaui kalkulasi logika.
Naisaburi membagi tiga level penerima cahaya ilahi. Pertama, Kegilaan total, kehilangan kontrol sepenuhnya. seperti pada orang gila pada umumnya kita temui. mereka kehilangan kontrol pada kesadaran mereka sendiri. Kedua, Uqala al-Majanin adalah definisi “gila” yang cukup untuk keluar dari norma kebiasaan pada kondisi orang normal, tapi “rasional” dan cukup untuk menelanjangi kepalsuan sosial. contohnya seperti Bahlul Majunun, dan Majnun Laila. Ketiga, Para Nabi dan Kekasih Allah adalah mereka yang menerima cahaya konstan tanpa kehilangan keseimbangan lahiriah
Lisensi Sosial: Gila Sebagai Senjata Kritik
Bahlul berada di level kedua: gila sekaligus bijak, liar sekaligus jernih. Di masyarakat Islam abad pertengahan, status “gila” memberi kebebasan unik. Orang gila bisa menertawakan elit, membongkar kepura-puraan, tanpa takut dihukum. Justru karena dianggap tidak bertanggung jawab, mereka bebas berkata jujur.
Keadaan ini menjadi semacam lisensi sosial yang menjamin keamanan bagi mereka yang dianggap gila, namun tetap leluasa melayangkan kritik bahkan dengan tonasi ekstrem. Mereka bisa mengolok kesombongan penguasa, menyingkap kebusukan pejabat, dan menertawakan kepura-puraan masyarakat. Kritik mereka mungkin terdengar absurd, tapi justru karena absurditas itulah pesan mereka menembus lapisan ego dan sampai ke hati.
Baca juga: Hari Valentine dan Makna bagi yang Jomblo
Di sinilah letak ironisnya. Zaman dulu, orang gila adalah mereka yang paling merdeka karena tak punya beban reputasi. Mereka punya 'lisensi' untuk jujur. Sementara sekarang? Kita adalah orang-orang yang paling terpenjara. Setiap langkah, kata, bahkan sudut foto kita harus sesuai dengan standar algoritma netizen agar tidak dianggap 'aneh'.
Hari ini, kita lebih memilih apatis dan diam daripada keluar dari zona nyaman. Kita berpura-pura tenang di tengah keramaian digital, padahal sebenarnya kita sedang merasa sunyi dan sepi di dunia nyata. AI, algoritma, dan filter telah memaksa kita hidup dalam dua wajah: satu wajah yang penuh pengikut demi reputasi, dan satu wajah asli yang kita sembunyikan rapat-rapat karena takut dianggap tidak normal
Algoritma dan Kehilangan Objek Asli
Kisah Bahlul terasa relevan dengan kegelisahan kita hari ini. Algoritma media sosial telah menjadi “akal kolektif” baru. Kita merasa waras jika mengikuti yang viral dan tren, dan merasa gila jika berdiri sendirian.
Kebenaran yang dulu bersumber pada cahaya ilahi kini diproduksi oleh angka. Jika banyak yang like, maka itu dianggap benar. Jika sepi perhatian, maka dianggap salah. Akhirnya kita kehilangan “objek asli” karena sibuk menatap hasil editan yang disukai massa. Lebih miris lagi, kebusukan yang dipamerkan di media sosial dan mendapatkan atensi dari banyak orang berupa like dan komen akan dianggap kebenaran dengan selimut zaman modern. Kewarasan baru itu dilahirkan berdasarkan viral.
Kita menjadi manusia filter, copy-paste, dan kehilangan kejujuran diri.
Saya termenung lama sambil mengetik tulisan ini. Sebenarnya, kita benar-benar waras, atau justru sedang terjebak dalam kegilaan kolektif yang tersusun rapi oleh algoritma? jujur saya tidak menyalahkan algoritma di zaman kita ini. Algoritma memang menyediakan panggungnya, tapi kitalah yang memilih untuk memakai topengnya.
Menuju Kalibrasi Terakhir
Bahlul mengingatkan: untuk melihat cahaya asli, kita harus berani mematikan lampu neon palsu—ekspektasi orang lain, tren, validasi sosial. Menjadi “gila” di mata dunia yang sakit mungkin adalah satu-satunya cara untuk tetap sehat secara spiritual.
Pertanyaannya: bagaimana kita membawa keberanian itu ke dalam keseharian kita—di tengah profesi, keluarga, dan tuntutan sosial? Apakah kita harus meninggalkan kenyamanan demi kewarasan, ataukah ada jalan untuk tetap berada di keramaian namun merdeka batin seperti Bahlul?
Itulah yang akan kita renungkan bersama di bagian penutup seri ini.